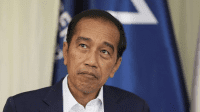Jejak Hitam di Balik Kasus Pertamina

Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra
Pemerhati Intelijen
FORUM KEADILAN – Suasana tiba-tiba menegang ketika Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama Pertamina, membuka kalimat yang membuat pengunjung menahan napas di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 27/10/2025. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata: “Saya mendapat tekanan dari dua tokoh nasional agar memperhatikan perusahaan milik Moh Riza Chalid dan anaknya, Kerry”.
Ucapan itu seperti memukul gong baru dalam perkara yang telah berlarut setahun terakhir. Dua tokoh nasional yang oleh hasil penelusuran investigatif disebut berinisial PY dan HR, pejabat senior di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut mendekati Karen di sebuah resepsi keluarga di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Mereka duduk di satu meja, berbicara singkat, dan menitip pesan agar perusahaan Mohammad Riza Chalid (MRC), taipan minyak lawas yang dijuluki godfather gasoline, “diperhatikan”.
Yang mengherankan, pengakuan di ruang sidang itu berhenti begitu saja. Majelis hakim tak meminta klarifikasi lebih jauh, jaksa pun memilih diam. Seolah ada tembok halus yang memisahkan kesaksian dari kebenaran.
Jejak Lama di Sumur Baru
Kasus dugaan korupsi Pertamina periode 2018-2023 menyeret banyak nama. Jaksa Agung menyebut kerugian negara mencapai Rp285,7 triliun, menjadikannya salah satu skandal terbesar dalam sejarah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kasus ini tak hanya soal suap atau mark up kontrak, tapi juga soal korupsi kebijakan berupa penyimpangan di level direksi hingga kementerian.
Empat subholding Pertamina disebut terlibat, yakni PT Kilang Pertamina International, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Pertamina Hulu Energi. Di antara temuan besar, BPK menemukan proyek High Octane Pertalite (HIP) yang disusun Dirut PT Patra Niaga Alfian Nasution dan Direktur Mars Ega Legowo Putra, disetujui oleh Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan disampaikan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Proyek itu mengakibatkan kerugian Rp11,11 triliun.
Belum cukup, pembayaran kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite Ron 90 tahun 2022-2023 merugikan negara Rp13,118 triliun. Penjualan solar industri di bawah harga subsidi kepada 13 perusahaan swasta, termasuk PT Adaro milik Boy Thohir, menambah kebocoran Rp9,4 triliun. Dalam laporan yang sama, ditemukan pula praktik ekspor minyak mentah hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang seharusnya bisa diolah di kilang domestik, tapi justru dijual ke luar negeri lewat jaringan perusahaan perantara.
Sumber di internal BUMN migas menyebut, kebijakan-kebijakan itu tidak lahir murni dari pertimbangan teknis. Ada tekanan politik, surat rekomendasi tak resmi, hingga “memo pribadi” dari pejabat tinggi negara.
“Pertamina itu tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Selalu ada kepentingan di atasnya,” kata seorang mantan komisaris yang enggan disebut namanya.
Dalam sejumlah dokumen yang diperoleh Tempo, muncul nama Mohammad Riza Chalid sebagai sosok yang beberapa kali mengajukan proyek kerja sama dengan Pertamina melalui perusahaan-perusahaannya. Riza dikenal luas di kalangan bisnis minyak sejak era 1990-an, pemain impor BBM yang punya koneksi lintas rezim. Ia pernah disebut dalam kasus Mafia Migas pada 2015, tapi tak pernah benar-benar dijerat hukum.
Sumber dari aparat penegak hukum mengungkap, sebelum status tersangka MRC ditetapkan, seorang makelar kasus (markus) disebut beberapa kali bertemu MRC di sebuah hotel di Kuala Lumpur.
“Pertemuannya membicarakan kemungkinan pengamanan kasus,” kata sumber itu.
Setelah pertemuan, proses penyidikan sempat mandek selama tiga bulan, sebelum akhirnya kembali dibuka setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntaskan kasus BUMN tanpa pandang bulu.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana jejaring ekonomi, politik, dan hukum saling berkelindan. Di satu sisi, Pertamina menjadi mesin negara yang menguasai 60 persen peredaran energi nasional. Di sisi lain, perusahaan itu menjadi ladang perburuan rente bagi mereka yang memiliki akses ke lingkar kekuasaan.
Sejak lama, kursi direksi dan komisaris BUMN strategis ditentukan bukan semata oleh kinerja, tapi oleh peta politik. Dalam kabinet sebelumnya, posisi strategis di Pertamina dan anak perusahaannya disebut menjadi bagian dari “pembagian saham politik” untuk menyeimbangkan dukungan partai.
“Semakin dekat dengan kekuasaan, semakin besar peluang mengatur aliran bisnis,” kata seorang mantan pejabat ESDM.
Negara yang Bekerja di Balik Negara
Dalam teori politik klasik, Machiavelli menyebut adanya dua lapisan negara yakni yang resmi dan yang tersembunyi. Yang pertama bekerja melalui hukum dan lembaga, yang kedua melalui patronase dan ketakutan. Skandal Pertamina menunjukkan bagaimana negara bayangan itu bekerja dengan presisi.
Salah satu contoh nyata adalah memo yang beredar pada 2015. Surat itu ditandatangani SN, saat itu Ketua DPR RI, kepada Direksi Pertamina agar membayar tagihan PT Orbit Terminal Merak, sebuah perusahaan yang diduga terhubung dengan jaringan MRC. Padahal KPK kala itu telah memperingatkan adanya kejanggalan dalam kontrak sewa terminal BBM tersebut. Memo itu kemudian menjadi catatan tersendiri dalam laporan pengawasan internal, tapi tak pernah berujung penyelidikan.
Dari segi regulasi, apa yang terjadi jelas melanggar prinsip dasar tata kelola BUMN. Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menegaskan bahwa perusahaan milik negara harus dikelola profesional, transparan, dan bebas intervensi politik. Tapi praktiknya, garis itu terus digeser oleh kepentingan kekuasaan. Banyak kebijakan Pertamina yang seharusnya berbasis kajian bisnis, justru bergantung pada persetujuan informal tokoh politik atau pejabat kementerian.
Para analis ekonomi menyebut, inilah bentuk paling nyata dari korupsi struktural. Korupsi tidak lagi berwujud amplop, tapi melekat pada sistem keputusan. Ia hadir dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dengan alasan “stabilisasi harga” atau “penyesuaian pasar”. Negara pun perlahan kehilangan daya kendali atas sumber energinya sendiri.
Dalam konteks ini, perintah Presiden Prabowo Subianto agar Kejagung menuntaskan kasus BUMN “tanpa tebang pilih” menjadi ujian moral pertama bagi pemerintahannya. Prabowo ingin membongkar gurita rente energi yang sudah mengakar sejak dua dekade terakhir. Tapi publik tahu, membongkar mafia minyak sama artinya dengan membuka rahasia masa lalu banyak tokoh besar di lingkar kekuasaan.
Pertanyaannya, seberapa jauh keberanian itu bisa melangkah?
Hingga kini, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) belum menetapkan tersangka baru di luar Karen Agustiawan dan beberapa pejabat subholding. Nama-nama besar seperti mantan Menteri BUMN Erick Thohir maupun MRC masih sebatas “didalami”. Sementara dua tokoh nasional yang disebut Karen yaitu PY dan HR belum tersentuh.
Seorang jaksa senior di Gedung Bundar mengatakan, penyelidikan terhadap tokoh-tokoh besar kerap tersandera oleh “pertimbangan politik”.
“Setiap kali naik ke level pejabat tinggi, ada telepon, ada surat, ada permintaan agar ditunda,” katanya
“Padahal kalau mau jujur, akar kasus ini ada di situ,” ujarnya.
Kondisi itu menciptakan paradoks di tubuh hukum sendiri. Di atas kertas, Indonesia memiliki kerangka hukum antikorupsi yang kuat berupa UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dukungan publik yang luas. Tapi di lapangan, hukum justru kerap jadi alat kompromi.
Di sinilah tragedinya. Negara yang seharusnya menjadi penegak keadilan justru menjadi bagian dari sistem yang menjaga agar kebenaran tak sepenuhnya muncul.
Luka Energi dan Masa Depan Bangsa
Skandal Pertamina bukan hanya soal uang negara yang raib. Ia adalah potret betapa rapuhnya kedaulatan energi kita. Dalam satu dekade terakhir, produksi minyak nasional terus turun hingga di bawah 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan konsumsi melonjak di atas 1,3 juta barel. Ketergantungan pada impor BBM mencapai 70 persen.
Ketika impor dan distribusi dikendalikan oleh jaringan yang sama mulai politisi, pengusaha, dan markus, maka setiap kebijakan harga energi akan selalu dipenuhi konflik kepentingan. Negara membayar mahal untuk subsidi, tapi keuntungan mengalir ke segelintir pemain.
Filosofisnya, energi seharusnya menjadi alat kedaulatan ekonomi, bukan komoditas politik. Bung Hatta pernah menulis bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai bila rakyat menguasai alat-alat produksi. Tapi kini, alat itu dikuasai oleh jaringan tak kasatmata yang bersembunyi di balik perusahaan negara.
Bagi publik, kelelahan terhadap drama korupsi sudah mencapai titik jenuh. Dari kasus Century, Jiwasraya, Asabri, hingga Pertamina, pola yang sama berulang, dimana pejabat kelas menengah jadi tumbal, elite di atasnya menghilang.
Pemberantasan korupsi di sektor energi hanya akan berarti jika berani menembus lapisan teratas, mereka yang menitipkan memo, menekan direksi, dan memelihara markus. Tanpa itu, semua operasi hukum hanya kosmetik.
Jaksa Agung kini memegang bola panas. Di hadapannya bukan sekadar berkas perkara, tapi kepercayaan publik yang terus menipis. Bila keberanian itu gagal dibuktikan, maka negara akan kembali dikendalikan oleh bayangan lama yaitu jaringan rente yang hidup di setiap liter bensin yang kita bakar.
Dan ketika keadilan tak lagi punya nyala, sejarah akan mencatat bahwa republik ini pernah gagal melawan dirinya sendiri.*