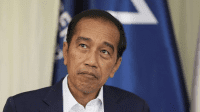Sumitro Djojohadikusumo dan Pergerakan Mahasiswa 1977-1978

Indra J Piliang
Sejarawan
FORUM KEADILAN – Sebagaimana banyak orang, tentu sebagai aktivis saya ingin menyampaikan pendapat terkait perkembangan masalah kebangsaan dewasa ini. Namun, saya tak mengerti kemana alamat yang hendak dituju untuk menyampaikan pendapat itu. Lalu bentuk dari pendapat itu sendiri apa, saya tidak paham. Apakah selembar kertas atau sebait pantun. Ataukah video yang diiringi gerak kaki atau tangan.
Gedung DPR/MPR RI sudah terlalu hiruk pikuk. Pagarnya berkali-kali ambruk. Kanal media sosial juga kepenuhan aspirasi. Dalam bentuk podcast dari yang melankolis, puitis, herois, kritis dan trengginas, sudah lebih dari setahun saya lakukan, sejak bergabung menjadi jurnalis senior di Forum Keadilan TV pada Juni 2024.
Berhubung waktu berpikir juga terbatas, saya putuskan cara ini: mengutip isi skripsi yang saya tulis.
Skripsi dengan judul “Koreksi Demi Koreksi: Aktivitas Pergerakan Mahasiswa Indonesia Pasca Malari Sampai Penolakan NKK/BKK (1974-1980)” saya tulis sejak tahun 1995 hingga 1997. Sepanjang sejarah Indonesia moderen, era 1970an tercatat paling banyak dan beragam aktivitas pergerakan mahasiswa, baik intra atau ekstra. Model student government dan pers kampus masih kokoh. Begitu juga dengan jumlah mahasiswa yang ditangkap paling banyak di akhir era.
Berhubung saya tak ingin menulis tafsir, saya nukilkan saja Sub Bab D dari Bab IV dengan judul “Dialog Mahasiswa dengan Tujuh Menteri Kabinet Pembangunan Il”.
Berikut isinya:
Intensifnya dialog yang dilakukan oleh mahasiswa Bandung dan mulai munculnya suara-suara kritis dari kalangan masyarakat kampus, dengan cepat mendapat tanggapan positif dari pemerintah.
Pada bulan Juli-Agustus 1977 dibentuklah sebuah tim yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional, serta beroriestasi di bidang akademis. Mereka terdiri dari Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai koordinator, yang beranggotakan Prof. Dr. Emil Salim, Prof. Dr. J. B. Sumarlin, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Prof. Dr. Ali Wardana, Prof. Dr. Ir. Mohammad Sadli, dan Dr. Syarif Thayeb. Mereka dikenal sebagai Team Dialog Tujuh Menteri.
Sebenarnya gagasan pembentukan tim ini bermula dari diskusi-diskusi internal yang dilakukan oleh Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DM UI) dengan para ‘Menteri Lulusan UI’. Diskusi internal itu bersifat tertutup, sehingga tidak terpublikasikan secara luas dalam pers umum. Diskusi yang dijembatani oleh Rektor UI Prof. Dr. Mahar Mardjono bertujuan untuk mencari kejelasan terhadap persoalan-persoalan yang aktual waktu itu.
Karena dinilai berhasil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis mahasiswa UI, Prof. Sumitro mengambil inisiatif untuk menggelarnya secara nasional, tanpa mempertimbangkan faktor ‘kedekatan psikologis’ yang terbangun dengan kalangan mahasiswa di kampus non UI. Presiden Suharto segera menyambut baik gagasan Prof. Sumitro itu, sehingga terbentuklah Team Dialog Tujuh Menteri.
Untuk itulah pada tanggal 23 Juli 1977 Presiden Suharto mengadakan pertemuan dengan beberapa menteri dan Kaskopkamtib di Bina Graha. Dalam pertemuan itu, Presiden Suharto menginstruksikan kepada para menterk dan Kaskopkamtib agar memberikan penjelasan lebih banyak kepada universitas-universitas dan akademisi-akademisi di seluruh Indonesia serta dosen-dosennya tentang perkembangan ekonomi yang telah dicapai selama Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I dan Pelita Il, serta apa yang hendak dicapai dalam Pelita berikutnya. Tugas utamanya ialah supaya kalangan kampus itu memperoleh bahan untuk dikaji.
Menurut keterangan Syarif Thayeb, kebijaksanaan itu dimaksudkan untuk mengajak mahasiswa berdialog dengan pemerintah. Hal ini juga dapat menutup salah informasi mengenai pembangunan dan dapat pula meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pembangunan. Mahasiswa diharapkan lebih banyak menyumbangkan pikiran mereka melalui saluran yang ada seperti DPR atau dialog langsung dengan menteri. Mahasiswa adalah partner pemerintah, karena itu tidak benar mahasiswa adalah penghambat jalannya pembangunan.
Penegasan di atas, makin memberi peluang kepada mahasiswa untuk bersikap. Di kalangan mahasiswa dan masyarakat sendiri sudah beredar isu tentang adanya Mafia Berkeley, yaitu para teknokrat lulusan University of Berkeley USA. Akibatnya, muncul opini di masyarakat bahwa seakan-akan kebijaksanaan pembangunan nasional makin diarahkan ke dalam kapasitas yang sangat menguntungkan kaum pemodal, dan makin memperparah posisi golongan ekonomi lemah.
Dialog tersebut berlangsung lancar di Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya, tetapi gagal di Bandung.
Umumnya para mahasiswa tidak mau berbicara tentang strategi pembangunan ekonorni jangka panjang, lebih mempersoalkan masalah korupsi, skandal, kemewahan, pemborosan, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Mereka juga mempermasalahkan UU Perlindungan Usaha Kecil, praktek kapitalisme yang tak pada tempatnya, pembangunan ekonomi yang terhindar dari korupsi, pemborosan dan monopoli, kesewenang-wenangan, dan lain-lainnya. Mereka lebih terfokus pada kasus-kasus yang terjadi.
Ketika dialog berlangsung di Yogyakarta, Team Tujuh Menteri kedatangan delegasi DM/Senat Mahasiswa (SM) Bandung yang diwakili oleh dua orang dari DM Institut Teknologi Bandung (ITB) dan DM ITT (Institut Teknologi Tekstil). Mereka menyampaikan ‘Memorandum DM/SM Bandung tentang Dialog’.
Isi Memorandum itu antara lain:
“Selama ini DM/SM Bandung, melalui kegiatan Gerakan Anti Kebodohan (GAK), telah cukup banyak berkomunikasi dengan kelompok-kelompok sosial di masyarakat dan unsur-unsur pemerintah: beberapa menteri, penyusun policy, dan penghimpun bahan-bahan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan lain-lain. Dan dari semua pembahasan kami tentang strategi pembangunan berdasarkan Pelita, GBHN, Data Penelitian, perbandingan dengan kenyataan yang ada, dan lain-lain, maka kami sampai pada kesimpulan bahwa: perlu diadakan perubahan strategi pembangunan yang lebih mengutamakan sifat kerakyatan dan manusia seutuhnya, yaitu melalui pendekatan pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Guna meningkatkan efektifitas dialog, maka pemerintah kami minta untuk menyiapkan dan menyampaikan materi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan kepada mahasiswa dan universitas, melengkapi kebijaksanaan resmi yang selama ini telah kami ketahui. Dan mahasiswa dan universitas supaya diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari materi tersebut, menyiapkan kritik dan usulan untuk melengkapi langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan. Rencana langkah-langkah perbaikan tersebut harus juga melibatkan semua unsur dalam masyarakat, baik dalam proses pemikiran maupun pelaksanaannya.”
Setelah mempelajari isi memorandum itu, Prof. Sumitro menyatakan menerima baik kandungan isinya dan berjanji untuk memenuhinya. Sesuai dengan janjinya, Prof. Sumitro mengirimkan bahan tertulis kepada DM/SM Bandung, sehari sebelum dilangsungkan dialog di UNPAD, Bandung.
Dalam pertemuan membahas materi itu, DM/SM Bandung sampai pada kesimpulan bahwa materi itu hanyalah hasil karya tulis Prof. Sumitro pribadi, yang bukan mencerminkan buah pikiran seluruh anggota Team Dialog Tujuh Menteri secara terpadu, karena pada sampul karya tulis itu tercantum nama Prof. Sumitro.
Selain itu, pemikiran Prof. Sumitro yang tertuang dalam naskah itu menyangkut Indonesia di tahun 2000, padahal yang dikehendaki mahasiswa adalah dialog yang menyangkut keadaan saat itu, di saat kerja menteri hanya 5 tahun.
Akhirnya, secara aklamasi tercapai kesepakatan untuk membuat rumusan yang diberi judul “Pernyataan Aksi Bengong”. Pernyataan tersebut dibacakan setelah Prof. Sumitro menyampaikan pidato pembukaan di Aula Universitas Padjajaran, Bandung.
Pernyataan Aksi Bengong itu berisikan, antara Iain:
“Bahwa dari dialog-dialog yang dilakukan antara ‘Team Tujuh Menteri’ dengan kalangan Perguruan Tinggi/Mahasiswa selama ini, ternyata tidak menjamin penyelesaian masalah terhadap segala keresahan yang dirasakan masyarakat seeara merata dewasa ini.
Bahwa dengan dialog-dialog tersebut lebih tampak sebagai pemadam situasi panas yang tengah berlangsung, sehingga hanya merupakan penyelesaian semu yang setiap saat bisa tumbuh kembali penumpukan ketidakpuasan dikalangan masyarakat…”
Dalam bagian lain disebutkan, untuk memecahkan masalah bangsa yang mendesak, maka DM/SM se-Bandung mengusulkan, antara Iain:
(1)Perlu mewujudkan proses-proses “Pengambilan Keputusan” yang mampu melibatkan semua bagian dalam masyarakat, baik dalam proses perencanaan, maupun pengawasan sehingga tercipta suatu masyarakat dan pemerintahan yang demokratis,
(2)Perlu lebih diprioritaskan Pembangunan Watak Manusia pelaksana pembangunan dalam tahap-tahap Pelita-Pelita agar tercipta hubungan yang selaras antara rumusan-rumusan dan pelaksanaannya sehingga mampu menghindari kebocoran-kebocoran dalam proses pernbangunan,
(3)Perlu adanya suatu kemauan dan tindakan politik (political will) untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih, efisien dan adil.
(4)Perlu segera diumumkan kepada rakyat Daftar Kekayaan Pribadi Pejabat Pemerintah (DKP-3) dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi beserta seluruh keluarganya.
(5)Perlu segera diselesaikan kasus-kasus hukum tingkat tinggi, seperti kasus Pertamina, Budiaji, Sawito, Komando Jihad, Penembakan di Jalan Batu Jakarta, dan lain-lain guna menciptakan keadilan hukum yang merata bagi semua warga negara.
Setelah membacakan pernyataan sikap itu, seluruh mahasiswa Bandung meninggalkan ruangan sidang. Dialog dengan para menteri batal dengan sendirinya.
Adanya pernyataan tersebut menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat dan kalangan mahasiswa sendiri.
Heri Achmadi, calon Ketua DM ITB, menyayangkan bubarnya rencana dialog itu dan menganggap ‘mahasiswa telah mematahkan penanya sendiri’.
Sedangkan Prof. Sumitro dalam wawancaranya di TVRI juga menyayangkan kejadian di Bandung itu. Prof. Sumitro mengalami kesulitan dalam merangkul pihak mahasiswa untuk terlibat dalam proses pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah, sesuai dengan grand design yang dibuat oleh pemerintah melalui Repelita, kendala-kendala dalam pelaksanaan di lapangan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah, yang terlihat begitu gamblang oleh mahasiswa, telah menjadi celah tersendiri bagi mahasiswa untuk menyodorkan konsep alternatif, bukan menerima ‘penjelasan resmi’ pemerintah lewat dialog Team Tujuh Menteri.
Begitulah nukilan dari skripsi saya, lebih dari 30 tahun silam. Ujung dari aktivitas demi aktivitas pergerakan mahasiswa era itu sudah bisa diketahui: seluruh kampus bergerak, para pimpinan gerakan mahasiswa di setiap kampus ditangkapi, pledoi-pledoi hebat lahir, student government dibunuh, pers mahasiswa dilindas, dan lebih dari satu dekade gerakan mahasiswa beralih ke kelompok studi dan advokasi ekstra kampus.
Tentu saya tidak punya pendapat terkait apa yang perlu dilakukan pemerintah sekarang dalam menghadapi aksi massa dan massa aksi, terutama gerakan mahasiswa. Nukilan ini saja mungkin sudah kepanjangan. Cukup sekian.*